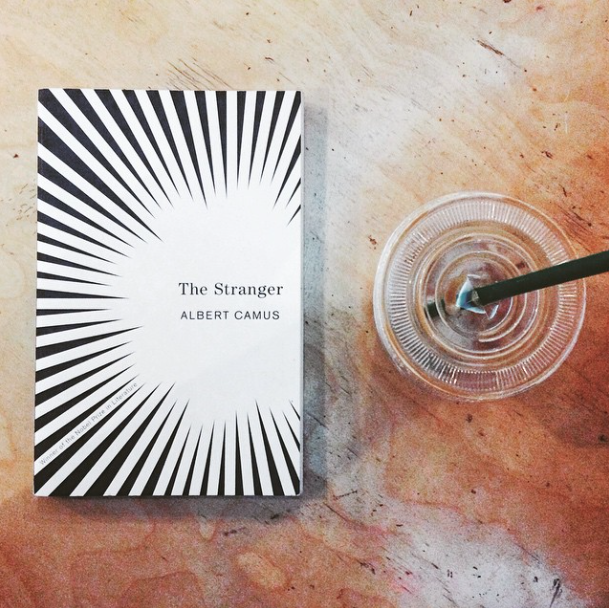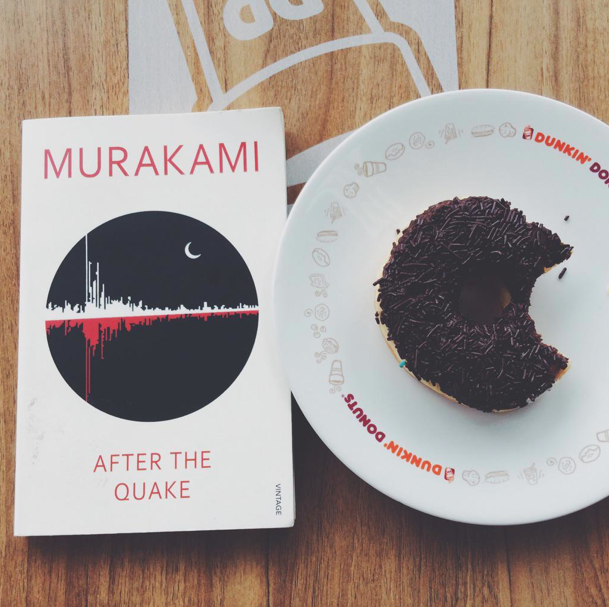Seorang pria melihat ibunya yang baru saja meninggal sedang disemayamkan, dan ketika seluruh pelayat hadir dengan wajah muram dan airmata menetes di pipi mereka, pria tersebut sama sekali tidak menangis. Bahkan, ia tidak sedikit pun menunjukkan tanda-tanda bahwa ia bersedih atas kematian ibunya. Seolah-olah ibunya yang sedang terbujur kaku sebagai mayat itu bukanlah ibunya, melainkan sebatang pohon yang baru saja ditebang, atau seekor lalat yang baru tuntas ditepuk.
Albert Camus memulai novela berjudul The Stranger ini dengan menampilkan gambaran karakter yang sangat kuat, sekaligus barangkali nyeleneh dan agak kurang masuk akal bagi sebagian orang. Terutama mereka yang berpikir bahwa manusia seharusnya merasakan emosi begini atau begitu.
Bukan hal keliru, memang, jika sebagian yang membaca The Stranger akan menganggap si lelaki yang berperan sebagai tokoh utama tersebut mengidap kelainan jiwa karena tidak menangis bahkan tidak menunjukkan tanda-tanda emosional sedikit pun saat melihat mayat ibunya, atau saat mendapat kabar bahwa ibunya meninggal. Bahkan, ia tidak ingat kapan tepatnya ibunya meninggal, hari ini atau kemarin, kemarin atau hari ini. Baginya sama saja.
Saya katakan bukan hal yang keliru, karena tokoh-tokoh lain di dalam The Stranger pun beranggapan demikian. Dapat dilihat ketika si tokoh utama terlibat masalah hukum setelah di siang bolong, di tepi pantai tempat ia berlibur bersama beberapa temannya, ia menembak mati seorang Arab. Lima tembakan di tubuh bagian depan.
Saat ditanya di persidangan tentang alasannya menembak laki-laki Arab tersebut, si tokoh utama awalnya diam karena tiba-tiba ia merasa jawaban yang akan berikan bakal terdengar sangat konyol di khayalak persidangan. Namun, ia tetap harus menjawab, karena ia pun ingin menjawab. Dan, benar saja dugaannya, saat ia memberikan jawaban atas pertanyaan itu, semua orang tertawa, termasuk jaksa penuntut umum.
Jawabannya ketika ditanya mengapa ia menembak mati laki-laki Arab tersebut adalah karena ia merasa sinar matahari pada saat itu sangat menyengat dan ia merasa pusing dan akhirnya ia pun menarik pelatuk dan menembak korban.
Semua orang merasa si tokoh utama memiliki kelainan jiwa. Apalagi ketika jaksa penuntut umum menyampaikan hasil penyelidikannya. Ia menemukan dan menyampaikan di persidangan bahwa si tokoh utama-yang telah jadi tersangka pada saat itu-diketahui lewat saksi-saksi, tidak menangis sama sekali dan tidak menunjukkan tanda-tanda emosi ketika menghadiri pemakaman ibunya. Bahkan, si tokoh utama pergi berkencan dengan seorang perempuan keesokan harinya dengan kondisi bahagia, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Seolah ibunya tidak pernah meninggal.
Dengan cerdas, Albert Camus menggiring pikiran kita hingga berada di posisi yang barangkali sama seperti tokoh-tokoh lain di dalam cerita. Seperti mereka, kita akan melihat si tokoh utama ini sebagai orang yang mengidap kelainan jiwa. Jangan-jangan ia pernah mengidap trauma masa kecil atau semacamnya, pikir kita.
Namun, kenyataannya si tokoh utama tidak mengidap trauma masa kecil atau apapun (setidaknya dari yang terlihat pada teks). Ia, dengan pemikirannya sendiri, memang merasa tidak ingin menangis. Tidak ada hal yang mendorong ia untuk menangis. Kematian Maman, ibunya, adalah sesuatu yang baginya normal-normal saja. Jika hari ini ibunya mati, atau kemarin, atau besok, atau tahun depan, sama saja. Semuanya tetap akan berjalan normal dan seperti biasa. Kematian ibunya bukanlah peristiwa yang signifikan.
Tidak sulit memahami jalan pikiran si tokoh utama di novela The Stranger (atau jalan pikiran pengarangnya) ketika kita mengetahui bahwa Albert Camus adalah seorang eksistensialis (silakan cari di Google apa itu eksistensialis). Meski tidak tampak di awal-awal cerita, pada akhirnya kita akan mengerti mengapa si tokoh utama memiliki jalan pikiran demikian dan mengambil tindakan-tindakan seperti di dalam cerita.
Membaca The Stranger Albert Camus mengingatkan saya pada novel-novel dan cerita-cerita pendek Haruki Murakami. Saya bahkan merasa mereka seperti abang-beradik. Camus abangnya, Murakami adiknya. Bisa kita bilang mereka berdua adalah eksistensialis. Tidak sulit mengetahuinya. Hanya dengan melihat tindakan dan cara berpikir tokoh utama dalam novel mereka, hal tersebut dapat terlihat.
Yang lebih ingin saya soroti dan bahas dari novela setebal 120 halaman ini adalah, kesederhanaan bahasanya. Berkali-kali saya berpikir bahwa pengarang-pengarang sekelas pemenang Nobel Kesusastraan pastilah memiliki karya-karya dengan bahasa yang berat. Bahasa yang berat maksud saya adalah pemilihan kata yang tidak lazim. Seperti novel yang dijejali kata-kata langka dari dalam kamus.
Namun, The Stranger sama sekali tidak demikian. Saya menyelesaikan membaca The Stranger hanya dalam beberapa jam. Mungkin tidak lebih dari tiga jam. Salah satunya karena bahasa Camus sangat mudah dipahami. Tidak ada kata-kata dalam Bahasa Inggris yang sulit, yang membuat saya mesti mengubek-ubek Google Translate untuk dapat memahami maksudnya.
Begitu pula dengan plot. The Stranger tak menggunakan model lain selain bentuk yang linear. Alur maju. Camus tidak menawarkan permainan flashback, foreshadowing, atau fragmen-fragmen yang rumit. Kisah tokoh utama yang dianggap memiliki kelainan jiwa oleh tokoh-tokoh lain di dalam cerita dikisahkan dengan cara yang amat sederhana.
Kadangkala saya berpikir bahwa penulis-penulis yang matang memang akan menuju bentuk dan cara yang sederhana. Seperti orang bijak atau orang pintar yang dapat menyampaikan hal rumit lewat pernyataan-pernyataan sederhana. Orang yang kerap menggunakan bahasa rumit, menurut saya, justru adalah orang yang tak benar-benar paham dengan apa yang ingin ia ucapkan sendiri.
Meski demikian, meski dengan bahasa dan alur yang sederhana, kita tahu apa yang dimunculkan oleh Camus lewat tokoh utama di The Stranger bukanlah hal yang sederhana. Camus menggali hingga ke dalam jiwa manusia, lalu memunculkan ke permukaan pertanyaan demi pertanyaan yang barangkali, secara sadar maupun tidak, menghantui kita semua. Mengapa seseorang harus punya tujuan hidup? Apakah tujuan hidup itu? Apakah hidup itu sendiri dan apakah itu kehidupan? Apakah kematian?
The Stranger juga membuat kita bertanya dan berasumsi, barangkali apa yang disebut kelainan jiwa hanyalah kewarasan dalam perspektif lain. Saya sering menduga dan curiga, jangan-jangan orang gila, atau yang setidaknya kita kerap sebut orang gila, hanyalah orang yang punya bentuk kewarasan yang berbeda dengan kita, manusia ‘waras’. Orang gila atau orang yang punya kelainan jiwa hanya memiliki dunia yang berbeda dengan kita. Dan, tentu saja, itu bukan hal yang aneh.
Lalu, jika benar demikian, apakah salahnya memiliki dunia yang berbeda? Apakah salahnya menjadi gila di dunia yang waras, atau menjadi waras di dunia yang gila? Bukankah waras dan gila hanya masalah mana yang lebih mendominasi? Seperti orang gila yang berada di dunia orang waras tidak dapat disebut orang waras, apakah orang waras yang diletakkan di dunia penuh orang gila tidak boleh disebut orang gila? ***