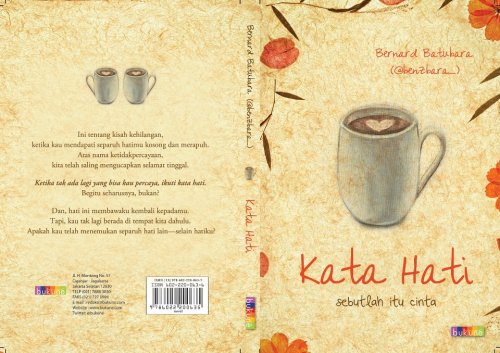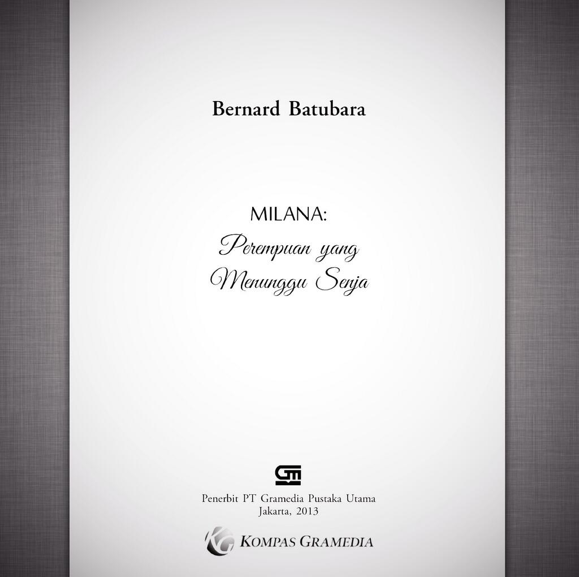Senja di Jembrana
Menunggu adalah perkara melebarkan kesabaran dan berhadap-hadapan dengan risiko ketidakhadiran. Itu yang dikatakan oleh ibu sehari sebelum dia meninggal. Saat itu, saya tidak tahu ia sedang berbicara tentang ayah yang pergi meninggalkan kami dan tidak pernah kembali lagi. Namun sekarang saya paham semuanya. Terutama karena saya mengalami sendiri perasaan yang dulu ibu alami.
Saya rindu perempuan itu. Perempuan ke-dua setelah ibu yang mampu membuat saya rela menjadi seorang penanti, seorang penunggu. Seseorang yang menghabiskan waktunya hanya untuk menunggu. Mendedikasikan setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun untuk menyambut sebuah kedatangan kembali. Untuk mendengar sebuah ‘Halo, ini aku, sudah pulang.’
Tetapi ia tidak pernah datang.
Terakhir saya melihatnya di atas feri yang sedang menambatkan diri di pelabuhan Gilimanuk. Saat itu, di waktu yang bersamaan saya melihat sepasang kekasih yang tampaknya turis domestik, turun dari feri. Mata saya tertumbuk pada mereka karena wajah mereka berdua terlihat sangat bahagia. Seperti pasangan yang akan berbulan madu. Kontras dengan kondisi hati saya yang sedang sangat sendu. Atau mungkin saya hanya terlalu mendramatisir.
Tidak, hati saya memang sedang biru.
Namun tidak sepekat warna biru yang melekat di sekujur permukaan kanvas perempuan itu.
Saya tidak tahu apakah dia memang seorang pelukis atau hanya seseorang yang gemar menggambar. Tetapi lukisannya sangat bagus. Sungguh. Saya bukan orang yang paham bagaimana menilai sebuah karya seni, tetapi mata tidak bisa dibohongi, bukan? Dan mata saya selalu seolah meleleh setiap melihat lukisan yang ia buat. Bola mata saya mendadak dua batang lilin bundar yang tersiram cahaya hangat yang memancar dari gambar di kanvas perempuan itu. Gambar yang selalu berwarna jingga.
Gambar yang selalu senja.
Perempuan itu tidak pernah melukis benda lain selain matahari yang tenggelam. Tidak pernah selain senja. Tidak dua gunung sejajar dan hamparan sawah serta langit dan burung-burung seperti yang diajarkan sejak duduk di bangku TK. Tidak perempuan telanjang seperti yang terpampang di adegan film Titanic. Tidak karikatur berwujud presiden atau pejabat dengan pose dan bentuk aneh seperti setiap hari tercantum di koran-koran lokal maupun nasional. Tidak gambar-gambar abstrak dan surreal seperti lukisan Salvador Dali atau Max Ernst (saya tahu nama-nama itu dari seorang teman yang kuliah di bidang seni). Perempuan itu hanya melukis senja. Selalu senja.
***
“Senja di Jembrana sangat indah.” kata perempuan itu.
“Senja di tempat lain juga.” kata saya.
“Iya. Tapi di sini lebih indah.”
“Apa bedanya?”
Perempuan itu menurunkan tangannya dari kanvas. Menghela napas dan melemparkan pandangan lebih jauh. Saya bisa melihat angin mampir di lehernya yang bersih, berputar-putar mengitarinya seakan ia pusat gravitasi untuk unsur-unsur alam di sekitarnya. Saya rasa saya juga mulai turut berputar di orbitnya.
“Mungkin karena ini adalah senja pertama yang saya lihat di daerah dengan zona waktu yang berbeda.”
“Oh, kau bukan asal sini?”
“Tidakkah itu terlihat?”
Saya mengangkat alis. “Ya, sedikit.”
Ia melanjutkan melukis. Menyapukan kuas kecilnya. Kuasnya bergerak begitu lancar seakan benda itu adalah bagian dari jari-jarinya sendiri.
“Kau sedang menunggu?” saya bertanya lagi.
Perempuan itu menghentikan gerak jarinya. Kemudian menarik napas cukup dalam sehingga bahunya yang kecil tampak terangkat. Ia melumat beberapa menit waktu dalam heningnya, sebelum akhirnya ia menjawab pertanyaan saya.
“Dari mana kau tahu?” ia balik bertanya.
“Hanya menebak.” jawab saya.
Ia kembali menyapukan kuasnya di atas kanvas. Kepalanya bergerak miring seakan mengikuti alur garis halus yang sedang ia bentuk. Dari samping, saya melihat bibir tipisnya menyunggingkan senyum. Senyumnya itu, seakan melontarkan berjuta rahasia yang mengundang untuk diungkap. Saya terpaku sejenak. Mata perempuan itu kecil, terbungkus kelopak mata tanpa lipatan seperti mata khas penduduk daerah asia timur. Mungkin dia seorang cina. Mungkin campuran bugis atau manado, karena kulitnya sangat putih. Lukisan yang ia buat menjadi sangat kontras dengan warna tubuhnya.
Ada yang unik dari senja di tanah Jembrana. Senja di sini hampir selalu datang bersama formasi awan cumolonimbus dan fibratus cirrus. Kadang hanya salah satu di antaranya, kadang pula keduanya. Semburat jingga dari matahari yang merambat turun bercampur dengan serat-serat putih awan fibratus cirrus dan menjadi pemandangan yang luar biasa. Seperti lukisan alam di hamparan langit biru tua. Setiap ke Jembrana, selalu disambut dengan senja yang serupa. Dan senja itulah yang dilukis oleh perempuan dengan kuas itu.
Perempuan yang melukis senja. Dia membereskan alat lukisnya dan melangkah pergi meninggalkan saya yang masih berdiri diam. Saya tidak bisa memanggil dia. Seakan-akan suara saya seketika hilang dan hanya bisa menatap punggung rampingnya menjauh.
Saya belum sempat menanyakan namanya.
***
Aku menunggu lelaki itu. Lelaki asing yang selalu memotret senja.
Sebelum ini, aku tidak pernah menunggu. Aku benci menunggu. Menunggu adalah perbuatan yang sia-sia. Menunggu adalah tindakan pasif dan melelahkan. Bagiku, menunggu adalah pertanda kelemahan. Bahwa tidak ada hal lain lagi yang bisa dilakukan selain duduk, diam, dan berharap segala yang diinginkan akan datang. Sungguh non sense.
Aku lebih suka mengejar. Mengejar adalah tindakan aktif dan tidak membosankan. Dengan mengejar, aku beberapa langkah lebih dekat kepada apa yang aku inginkan. Aku memotong waktu, memangkas jarak. Aku bisa menentukan kapan aku akan sampai di tujuan. Aku bisa memperkirakan seberapa jauh atau seberapa dekat lagi diriku dari apa yang aku ingin raih. Waktuku terpakai dengan tidak sia-sia.
Namun kali ini, aku tidak bisa mengejar dia.
Aku tidak mampu mengejar dia. Dan pertemuan-pertemuan bersamanya, masih terekam dengan jelas di dalam kepalaku.
“Hai.” lelaki dengan kamera itu menyapaku. “Kita bertemu lagi.”
Aku menundukkan kepala, mataku menatapnya. “Eng, iya..”
“Kau sering ke sini?”
“Tidak. Baru belakangan ini saja.”
“Dari Surabaya juga?”
“Iya. Kamu juga?”
Lelaki itu menganggukkan kepalanya. Ia tersenyum. Rahangnya yang tegas bertumpu pada batang lehernya yang besar dan kokoh. Bibirnya tipis dan senyumnya membentuk sudut yang tajam di kedua pipinya yang tirus dan dihiasi rambut-rambut halus. Ia membungkus tubuhnya dengan kaus putih dan bagian atas kakinya dengan celana kargo selutut berwarna coklat tua. Rambutnya tampak berantakan tertiup angin laut, namun aku masih bisa melihat matanya yang menyipit. Di sepasang matanya, senja terpantul.
“Apa yang kamu potret?”
Lelaki itu memalingkan wajahnya ke laut. “Tidakkah jelas terlihat?”
“Senja?” aku menaikkan alis.
Ia mengangkat kameranya sejajar mata dan mulai membidik. Aku merasakan ada debar yang aneh di dadaku saat melihat lelaki itu tampak asyik dengan dunianya sendiri, menjebak pemandangan senja lewat lensa kameranya.
***
Itu pertemuan ke-dua saya dengan perempuan pelukis senja.
Kali ini saya sudah tahu namanya. Milana. Ia bercerita mengapa ia melukis senja. Dan mengapa ia selalu melakukannya di atas feri yang menyeberang Selat Bali, dari Banyuwangi ke Jembrana. Ia sedang menunggu kekasihnya. Ia yakin suatu saat kekasihnya akan datang di tempat ia menunggu sekarang. Ia tidak tahu kapan. Tetapi ia berkata kepada saya, bahwa ia bukan saja yakin, tetapi ia tahu, bahwa kekasihnya itu akan datang.
“Pada pertemuan ke-dua, aku membawa alat lukisku, dan menemani ia memotret senja.” Milana tersenyum. “Sejak itu, kami berjanji untuk selalu bertemu di atas feri ini dan sama-sama merekam senja. Dengan cara kami masing-masing. Dia memotret. Aku melukis.”
Namun entah mengapa, di balik senyumnya yang tersungging dan tampak bahagia ketika ia mengingat-ingat kekasihnya, saya melihat ada yang kosong di matanya. Seperti sebuah ruang yang telah ditinggalkan oleh penghuninya begitu lama. Seperti sebongkah kenangan yang kehilangan intisarinya. Mata Milana terlihat kehilangan nyawa, tak bercahaya, tak secerah senja yang setiap hari dilukisnya.
Saya merasakan ada yang tidak benar dengan dirinya.
“Lalu?” saya meminta Milana untuk bercerita lebih panjang lagi.
“Lalu? Lalu, tentu saja kami jadi sering bertemu. Dia memotret. Aku melukis. Terus seperti itu. Dia bahagia. Aku bahagia. Terus seperti itu.”
“Lalu sekarang dia di mana?”
Tangan Milana berhenti. Mengambang di udara. Ujung kuasnya mengawang tiga senti dari permukaan kanvas. Saya menunggu penjelasan darinya. Ia masih diam. Bibirnya terbuka, tetapi tidak ada satupun kata yang keluar. Jemarinya yang panjang dan kurus gemetar. Sangat jelas terlihat. Saya mulai khawatir.
“Maaf. Kalau kamu tidak mau cerita juga tidak apa-apa.”
Milana menarik napas. Ia menundukkan kepalanya seraya menurunkan kuas dan meletakkan tangannya di atas paha. Saya masih menunggu respons darinya.
“Aku tidak tahu dia di mana.” akhirnya perempuan pelukis senja itu kembali bicara. “Tapi aku tahu, dia pasti datang.”
“Tapi, bagaimana kamu bisa-“
“Aku tahu dia pasti datang!” Milana menekankan kuasnya ke kanvas dengan keras sehingga membuat coretan panjang di lukisannya. “Dia. Pasti. Datang.”
Setelah itu, Milana membereskan alat lukisnya dan bergegas meninggalkan saya. Lagi-lagi, sebuah pertemuan yang tidak usai. Terasa jelas ada kegusaran di nada bicara Milana ketika saya mempertanyakan keyakinannya tadi. Saya tidak tahu ada sesuatu apa yang terjadi di antara ia dan kekasihnya. Tetapi saya tahu, itu sangat mengganggu pikiran Milana.
***
Saya sedang membuka halaman demi halaman majalahtravel langganan sebelum akhirnya mata saya berhenti pada sebuah halaman. Rubrik yang sedang saya baca membahas topik khusus tentang travel photographer dan menulis daftar Most Famous Travel Photographer di Indonesia. Di halaman yang sedang saya lihat, terpampang foto seorang lelaki dengan kamera yang menggantung di leher. Lelaki itu mengenakan kaus putih dan celana kargo selutut berwarna coklat tua. Ia tersenyum dengan tangannya dimasukkan ke dalam saku celana.
Areno Adamar: Lelaki Perekam Senja, begitu tajuk artikel yang menyertai foto tersebut. Are, begitu nama panggilannya seperti yang ditulis, dikenal sebagai travelphotographer muda yang sangat gemar memotret senja di berbagai tempat yang ia datangi, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Are adalah a rising star di kalangan travel photographer. Foto-foto senjanya adalah foto-foto senja terindah yang pernah orang lihat. Ada semacam kekuatan magis yang menyedot siapapun yang melihat foto-fotonya. Foto-foto senja Are sangat sederhana, tetapi di setiap sudut gambarnya menyimpan atmosfer yang aneh yang membuat orang-orang betah berlama-lama hanya memperhatikan gambar yang ia buat.
Saya melanjutkan membaca. Dan kemudian menemukan sesuatu yang cukup membuat terhenyak.
Sayangnya, sekarang penikmat pemandangan matahari tenggelam di nusantara tidak bisa lagi melihat karya-karya potret senja Are yang fenomenal. Kecelakaan feri dua tahun lalu merenggut beberapa nyawa, termasuk sang lelaki perekam senja yang memiliki senyum manis ini. Are meninggal dalam kecelakaan feri yang menyeberang dari pelabuhan Padang Bai Bali ke pelabuhan Lembar, Lombok. Perjalanan yang seharusnya menjadi bagian akhir dari rangkaian tur LANSKAP, komunitas travel photography yang dirintis oleh Are, berubah menjadi tragedi yang memilukan. Are ditemukan tidak bernyawa lagi, dengan kamera masih tergantung di lehernya.
Sampai di sana, saya berhenti membaca dan menahan napas. Saya teringat Milana. Mungkinkah lelaki perekam senja yang ia ceritakan adalah Are? Mungkinkah lelaki yang ia tunggu setiap hari di atas feri Banyuwangi – Jembrana sambil melukis senja adalah lelaki yang fotonya terpampang dalam artikel ini? Mungkinkah Milana menunggu kedatangan orang yang sudah mati?
Saya menutup majalah itu. Di luar, langit sedang sangat jingga. Saya ingin segera bertemu Milana.
***
“Kamu menunggu lelaki ini?”
Pria itu menyodorkan sebuah majalah ke hadapanku. Di halaman yang ia buka, aku melihat foto dia. Dia, lelaki yang merekam senja, lelaki yang aku tunggu. Areno, lelaki yang aku sayang dan lelaki yang berjanji untuk menemuiku sepulangnya ia dari rangkaian tur panjang bersama teman-temannya. Lelaki yang tidak pernah ingkar janji. Lelaki yang tidak pernah terlambat satu menit pun saat menemuiku di atas feri ini.
“Dia sudah meninggal. Kamu tahu itu?” pria itu kembali berbicara.
Aku tidak suka nada bicaranya.
Pria itu melangkah mendekatiku. “Lelaki yang kamu tunggu, sudah meninggal, Milana. Apa yang kamu lakukan?”
“Menunggu.”
“Dia tidak akan kembali. Kamu tidak mengerti? Dia sudah tidak ada lagi.”
“Dia ada. Dia sudah berjanji. Are tidak pernah ingkar janji!”
***
Saya tidak bisa melihat perempuan itu seperti ini terus. Milana harus sadar dan menerima kenyataan bahwa apa yang ia tunggu selama ini tidak akan pernah datang kembali. Namun, ia menolak dan mementahkan semua kata-kata saya. Ia tidak bisa menerima bahwa jelas-jelas Areno, lelaki perekam senja, sudah meninggal dalam kecelakaan feri dua tahun lalu.
Milana bersikeras bahwa Areno tidak meninggal. Dia hanya pamit pergi dan berjanji akan menemuinya lagi di atas feri dari Banyuwangi ke Jembrana, seperti biasanya.
“Lelaki itu tak akan kembali, Milana!” saya merampas kanvas perempuan itu dan membantingnya, menginjaknya hingga rusak. “Dia tidak seperti senja yang kamu lukis ini. Dia tidak akan datang lagi.”
“Kau.. Apa yang kau lakukan?!”
Milana berlutut dan menyambar kanvasnya. Sontak airmatanya keluar dan membuat saya semakin merasa bersalah. Namun, saya harus melakukan sesuatu. Tidak ada cara lain untuk menyadarkan Milana, selain merusak ritual yang membuat ia terjebak dalam bayangan janji kehadiran Areno kembali.
Lalu, seperti yang sudah-sudah, Milana pergi meninggalkan saya dengan membawa kanvasnya yang sudah saya rusak.
Kali ini, ia pergi dengan berlari cepat dan airmata yang berderai.
***
Saya rindu perempuan itu. Perempuan ke-dua setelah ibu yang mampu membuat saya rela menjadi seorang penanti, seorang penunggu. Seseorang yang menghabiskan waktunya hanya untuk menunggu. Mendedikasikan setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun untuk menyambut sebuah kedatangan kembali. Untuk mendengar sebuah ‘Halo, ini aku, sudah pulang.’
Tetapi ia tidak pernah datang.
Milana tidak pernah datang.
“Halo.”
Sayup-sayup suara perempuan terdengar dari balik punggung saya.
“Sedang menunggu sesuatu?” perempuan ini bertanya.
Saya menghentikan jemari di atas buku kecil tempat saya mencatat macam-macam hal. Kemudian menarik napas cukup dalam dan melumat beberapa menit waktu dalam hening, sebelum akhirnya saya menjawab pertanyaan perempuan asing ini.
“Dari mana kau tahu?” saya balik bertanya.
“Hanya menebak.” jawab dia.
***