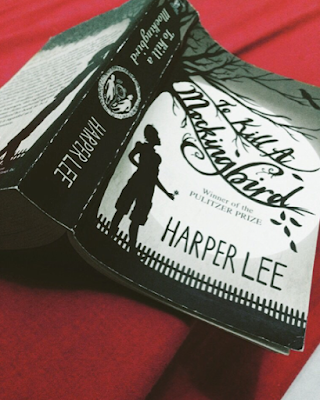Seratus lima puluh halaman pertama novel ini membuat saya bosan. Alur yang lamban dan arah cerita yang tidak jelas mau ke mana, mau tidak mau memancing saya berpikir keras mengapa novel ini menjadi salah satu novel terbaik dunia sepanjang masa. Saya menunggu dan menunggu dan setiap sepuluh halaman, saya menghela napas panjang, mencoba menahan diri untuk tidak menutup buku dan mengembalikannya ke rak di kamar saya. Untungnya, seperti yang sering terjadi, rasa penasaran saya lebih kuat daripada rasa bosan yang telah mendera sejak halaman pertama. Bermodalkan rasa penasaran tersebut, saya melanjutkan membaca buku pertama dan satu-satunya-sebelum lima puluh tahun kemudian prekuelnya terbit-dari penulis Amerika ini, yang sempat diganjar Pulitzer Prize tahun 1961. Novelnya sendiri terbit tahun 1960.
Harper Lee lahir tahun 1926 di Monroeville, Alabama, Amerika Serikat; ia juga bertumbuh besar di sana. Maycomb County, kota imajiner dalam To Kill A Mockingbird yang menjadi sentral seluruh cerita, disepakati oleh banyak orang diciptakan Lee berdasarkan tempat kelahirannya sendiri. Kota itu digambarkan sebagai kota yang penduduknya memiliki ciri khas masing-masing dan ciri khas tersebut lama-lama menjadi stereotipe, bahkan kemudian menjelma tuntutan bagi keturunan termuda untuk bersikap sebagaimana keluarganya dikenal.
Scout Finch, seorang gadis cilik yang menjadi tokoh utama novel, misalnya, di satu bagian diberitahu oleh anggota keluarganya untuk “Berkelakuanlah seperti seorang Finch.” Begitu pula dengan keluarga lain, yang telah mewarisi secara turun-temurun cara bersikap, karakter, termasuk hal-hal buruk yang telah dihapal seisi Maycomb County. Maka, adalah sah bagi seseorang menganggap jika kau seorang bernama belakang Cunningham, maka kau pasti miskin dan tidak mampu membayar makananmu sendiri. Menarik ketika saya tiba-tiba menyadari bahwa bisa saja Harper Lee menggunakan stereotipe pada keluarga-keluarga di Maycomb County sebagai pengantar menuju isu inti yang ia ingin angkat: rasisme.
Maksudnya begini, jika kau Cunningham dan berarti kau miskin, Crawford berarti kau tukang gosip, apakah itu berarti jika kau berkulit hitam maka kau pasti melakukan hal-hal menjijikkan yang dapat dilakukan seorang manusia, seperti misalnya mencari kesempatan memperkosa wanita berkulit putih?
To Kill A Mockingbird berjalan lamban bagi saya, sampai bagian pertama selesai dan bagian kedua dimulai. Atticus Finch, ayah Scout Finch, adalah pengacara. Ia sedang menangani kasus yang menimpa Thomas Robinson, seorang budak kulit hitam. Dari sini tempo cerita meningkat. Konflik barulah terasa, dan ketegangan terbangun. Salah satu bagian paling saya suka di novel ini adalah persidangan Atticus Finch. Semua orang tahu bahwa belum pernah tercatat dalam sejarah seorang budak kulit hitam menang dalam persidangan orang kulit putih. Meski demikian, Atticus Finch memberikan ‘perlawanan’ sengit bagi pihak pelapor, kelarga Ewell, yang salah satu anggota keluarganya, Mayella Ewell, mengaku telah diperkosa oleh Tom Robinson. Pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan Atticus kepada saksi-saksi dari pihak lawan. Lantai bawah ruang sidang diisi hanya orang-orang kulit putih dan di balkon berdiri orang-orang kulit hitam, semuanya menyimak jalan persidangan dengan perasaan yang sama seperti saya: tegang.
Saya sudah lupa bahwa novel ini sempat membuat saya bosan di seratus lima puluh halaman pertamanya. Akhirnya, saya dapat membaca hingga selesai.
Bagi saya, hal menarik dari To Kill A Mockingbird bukanlah isu rasisme yang ia usung, melainkan hal-hal lain yang ada di dalamnya. Misalnya soal parenting. Saya suka melihat bagaimana Atticus Finch mendidik anak-anaknya dengan selalu meladeni dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka-yang seperti anak-anak umumnya, merupakan pertanyaan-pertanyaan ‘dewasa’ melebihi usia mereka-tanpa berbohong. Misal saat Scout bertanya kepada Atticus, apa itu ‘rape’. Atticus juga mendidik anak-anaknya untuk bertanggungjawab dan ia senantiasa bersikap fair kepada Scout dan Jem Finch.
Meski bukan satu-satunya karakter favorit saya, Atticus Finch memang menarik banyak simpati. Ia laki-laki yang, tidak hanya dapat diteladani perilakunya sebagai orangtua, tetapi juga sikapnya sebagai manusia. Atticus berada pada posisi sulit. Ia orang kulit putih yang menjadi kuasa hukum budak kulit hitam. Ia seperti mengerjakan pekerjaan ‘kotor’, begitu orang-orang Maycomb County memandangnya. Ia juga dianggap pengkhianat karena tindakan pembelaaannya itu. Meski demikian, Atticus tidak pernah kehilangan empati dan sikap adilnya terhadap setiap orang yang ia kenal. Ia sama sekali tidak tampak marah atau kesal, apalagi ingin membalas, saat pasca persidangan Thomas Robinson, Mr. Robert Ewell memakinya di dekat kantor pos dan meludahinya. Anak-anaknya tidak menyukai hal tersebut tapi Atticus hanya berkata kepada mereka bahwa Mr. Ewell telah melalui hidup yang sulit dan di persidangan, Atticus telah membuatnya kehilangan harga dirinya di depan banyak orang, sehingga wajar Mr. Ewell melakukan hal itu terhadapnya.
To Kill A Mockingbird adalah novel tentang praduga. Tentang bagaimana manusia kerap membangun sangkaan-sangkaan dalam kepalanya terhadap manusia lain, dan ini seringkali terjadi karena kita tidak pernah benar-benar mengenal orang yang kita ‘dakwa’. Dan, sesering itu pula, dakwaan kita keliru. Harper Lee menunjukkannya lewat karakter-karakter seperti Mrs. Dubose yang kerap menyumpahserapahi Atticus kepada Scout dan Jem karena ayah mereka membela budak kulit hitam, namun ternyata Mrs. Dubose menyiapkan hadiah manis buat Jem setelah ia meninggal dunia. Ada pula Nathan “Boo” Radley, yang semenjak bagian awal novel digambarkan seperti orang gila yang mengurung diri di rumahnya selama puluhan tahun, ternyata adalah orang yang, seperti kata Scout, “…he was real nice.” dan sebagai respons ucapan anaknya tersebut, Atticus Finch berkata, “Most people are, Scout, when you finally see them.”
Yang membuat To Kill A Mockingbird bertahan hingga setengah abad adalah, saya kira, pesannya yang sangat universal. Isu rasisme tidak hanya terjadi di Amerika dan dengan demikian novel ini tidak hanya relatable dengan kondisi manusia-manusia di Amerika pada masa dulu hingga sekarang, melainkan seluruh orang. Lebih dari sekadar rasisme, seperti saya sebut sebelumnya, bahwa novel debut Harper Lee ini adalah tentang praduga. Kita tahu sama tahu, praduga tumbuh dan bermukim di balik tengkorak kepala kita. Bukan hanya persoalan kulit hitam dan kulit putih, tapi juga praduga yang melekat pada identitas-identitas lain: etnis, agama. Praduga-praduga terhadap identitas seorang manusia, terutama praduga yang buruk, sering menjadi bibit tumbuhnya konflik. Berapa kali konflik horisontal terjadi akibat penajaman stigma dan tidak dikelolanya praduga dalam tiap-tiap kepala manusia?
Hal terakhir dari novel ini yang menarik perhatian saya: bagaimana penulisnya memilih tokoh utama seorang gadis kecil. Scout Finch, saya kira, menjadi metafor yang digunakan Harper Lee untuk menunjukkan kemurnian dan kejernihan mata seseorang dalam memandang orang lain dan dunia. Anak kecil tidak bermain dalam praduga, mereka berkenalan dan bermain dengan siapa saja yang mereka senangi, siapapun mereka dan beragama apapun mereka. Orang dewasa lah yang merepotkan dirinya sendiri dengan praduga-praduga. ***