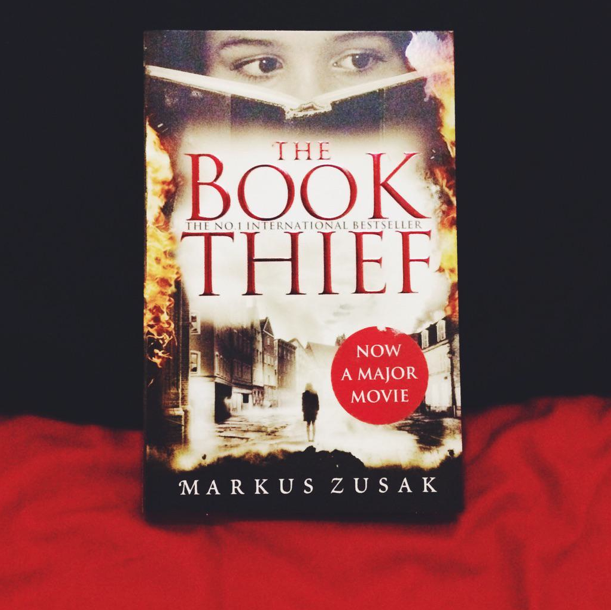Hal paling cerdas yang telah dilakukan Markus Zusak di novelnya The Book Thief, saya kira, adalah keputusannya untuk bercerita menggunakan sudut pandang Kematian. Andai Zusak tidak melakukannya dan bertutur memakai sudut pandang salah satu tokoh dalam kisah keluarga berlatar belakang perang Nazi Jerman itu, barangkali, sosok Liesel Meminger dan apa saja yang terjadi dengan orang-orang di sekitarnya tidak menjadi lebih menarik.
The Book Thief dibuka dengan deskripsi yang dilihat dari kacamata-dan digambarkan oleh-si narator utama: Kematian. Bab pertama pada bagian prolog novel tersebut diberi judul “Death and Chocolate”. Dengan sudut pandang orang pertama, Kematian menuturkan apa yang dia lihat, setiap kali terjadi kematian.
First the colours.
Then the humans.
That’s usually how I see things.
Or at least, how I try.
Zusak tidak memberitahu kepada pembaca bahwa yang sedang berbicara adalah Kematian, atau Malaikat Maut. Namun, lewat adegan-adegan terjadinya kematian manusia, tuturan “Aku”-narator saat melihat jenazah dan gerakannya menghampiri jenazah tersebut, menyaksikan jiwa jenazah itu melayang, lantas menangkap dan menyimpannya, kita tahu bahwa yang sedang berbicara sepanjang novel adalah Kematian.
Tokoh Kematian atau Malaikat Maut dibangun oleh Zusak menggunakan citraan yang berbeda dari persepsi kebanyakan orang atas kematian. Kematian, kita tahu, pada umumnya adalah sesuatu yang menakutkan. Menyeramkan. Menyebutkannya saja bikin bergidik. Namun, lewat tuturannya sebagai narator utama, Kematian di novel Zusak adalah sosok (sesuatu) yang lembut, bergerak dengan perlahan, bahkan indah. Jauh dari bayangan atau persepsi manusia atas kematian. Ini dapat dilihat dari bagaimana Kematian menyampaikan isi pikirannya, apa yang ia lihat, dan (bahkan) perasaannya. Atau, setidaknya, yang kita lihat sebagai perasaannya.
Di The Book Thief, Kematian adalah sesuatu yang hidup.
Lewat tuturan Kematian lah, kisah utama novel ini menguak, selapis demi selapis. Seorang gadis kecil yatim piatu bernama Liesel Meminger dititipkan kepada sebuah keluarga. Kelak, Liesel Meminger akan hidup dengan orangtua asuhnya, pasangan Jerman bernama Hans Hubermann dan Rosa Hubermann. Liesel Meminger sendiri adalah seorang Jerman. Kehidupan Liesel di keluarga barunya mudah sekaligus sulit. Mudah karena Hans Hubermann adalah laki-laki yang ramah dan menyenangkan. Sulit karena sebelumnya Liesel ditinggal oleh adik kandungnya yang tewas karena kecelakaan kereta api, dan ibu asuhnya, Rosa Hubermann, adalah perempuan yang keras dan kerap mengomelinya (namun belakangan kita tahu Rosa sebetulnya punya hati yang lembut dan sangat menyayangi Liesel).
Saya kira, keputusan Zusak menggunakan narator utama Kematian bukan tanpa alasan. Ia melakukannya tidak sekadar bertujuan agar ceritanya berbeda karena dituturkan lewat kacamata sosok non-manusia, melainkan terkait erat dengan isu dan peristiwa utama yang terjadi dalam novelnya, yakni Perang Dunia II di Eropa. Atau, sesuatu yang lebih spesifik lagi: Nazi Jerman dan Adolf Hitler.
Lewat narasi yang sangat mengalir, Zusak mengawinkan dua hal yang teramat kontras dalam novelnya: kekerasan dan keindahan. Cara bertutur Zusak, diwakili oleh Kematian sebagai narator utama, terasa lembut dan mengalun perlahan, bahkan narasinya terkadang terasa cantik. Lebih tepatnya, indah. Deskripsi adegan kematian, sesuatu yang terjadi pada detik-detik seorang manusia melepaskan nyawanya, terasa surealis namun indah. Seperti lukisan abstrak dengan warna-warna pastel nan lembut dan sederhana. Mengiringi keindahan dan kelembutan narasi tersebut adalah konteks cerita yang jelas-jelas keras: perang dunia, juga aktivitas kelompok Nazi Jerman. Kebrutalan mereka merusak rumah-rumah di sepanjang Himmel Street di kawasan rumah orangtua asuh Liesel Meminger dan pawai yang ujung-ujungnya adalah peristiwa pembakaran buku, menjadi sesuatu yang menegaskan kembali betapa hidup Liesel Meminger dan keluarga asuhnya, Hans-Rosa Hubermann, sangat sulit karena terkekang dan dibayangi oleh ancaman-ancaman.
Kian sulit lagi karena Hans Hubermann, meski ia seorang Jerman, bukanlah simpatisan Nazi. Berbeda dengan anak kandungnya yang telah mengabdikan dirinya untuk Nazi dan Hitler. Kembali, Zusak memasukkan konflik keluarga, yakni hubungan ayah dan anak yang memiliki prinsip hidup bertolakbelakang. Rosa Hubermann, sang istri dengan watak keras dan disiplin tinggi, pun merasakan dampak buruk dari peperangan dan kehadiran Nazi. Usaha cuci baju keliling Rosa terpaksa berhenti karena pada masa perang tak ada orang berpikir untuk menghabiskan uangnya membayar jasa pencucian baju.
Meski konteks yang diangkat terbilang berat (Perang Dunia, Nazi Jerman, Hitler, Yahudi) The Book Thief adalah novel remaja. Barangkali karena hal tersebut, Markus Zusak sadar bahwa ia tetap harus memberikan hiburan. Rudy Steiner, bocah lelaki penggemar atlet lari kulit hitam yang kemudian jatuh cinta pada Liesel Meminger, adalah salah satu karakter yang diciptakan Zusak untuk tujuan tersebut. Di sepanjang cerita saya dibuat tersenyum-senyum oleh tingkahnya dan interaksi Rudy dengan Liesel, juga bagaimana hubungan cinta monyet mereka terbangun dari rasa kesal, kejailan-kejailan, dan kenakalan-kenakalan.
Novel setebal 584 halaman ini benar-benar sebuah page turner. Seperti yang sempat saya bilang, narasi Zusak amat mengalir. Ia jarang menulis kalimat-kalimat panjang dengan kata-kata kiasan atau perumpaan yang sulit dicerna. Sebaliknya, kalimat-kalimatnya kerap pendek-pendek, menggunakan kosakata yang mudah dimengerti. Mungkin karena, lagi-lagi, The Book Thief adalah novel remaja (setidaknya di Goodreads dan beberapa situsweb, novel ini dikategorikan novel remaja).
Namun, justru di sana lah saya melihat kecerdasan Markus Zusak yang lain: kepiawaiannya menggabungkan isu berat dan kemasan novel remaja. Zusak tidak pretensius dengan menulis sesuatu yang berkoar-koar mengenai Nazi Jerman, Hitler, atau Perang Dunia II. Sehingga, novelnya tidak menjadi kumpulan fakta ataupun riset mengenai Nazi, melainkan literatur yang menyenangkan untuk dibaca.
Seingat saya, tidak banyak (atau bahkan belum ada?) novel remaja di Indonesia yang memiliki muatan seperti The Book Thief. Novel remaja dengan kemasan ringan dan bahasa yang mudah, namun mengandung konteks isu sosial, politik, atau sejarah. Saya bayangkan misalnya saja ada novel remaja dengan tokoh berusia empat belas tahun yang hidup di masa terjadinya kerusuhan antar suku di 1997, atau seorang gadis kelas enam SD yang bapaknya tahanan politik, dan semacamnya.
Jika ada yang menuliskan novel-novel seperti itu (saya berdoa semoga kelak ada dan banyak) tentu saja segmen novel remaja di Indonesia akan jadi lebih menarik, berwarna, dan menyenangkan. ***